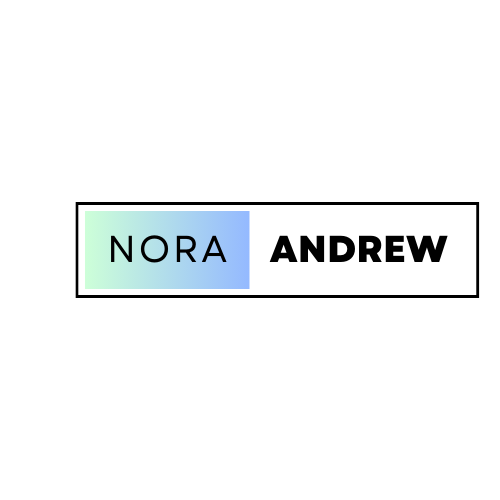Well minggu lalu temenku merekomendasikan 2 film terbaik, jika di artikel sebelumnya film yang tak tonton tentang romansa, yang ini sedikit berbeda. Judulnya My Oxford Year.
Jujur ya, waktu pertama kali nonton My Oxford Year, aku kira ini bakal jadi film romansa kampus luar negeri yang manis-manis aja. Tipikal: cewek pintar ke luar negeri, ketemu cowok charming, jatuh cinta, lalu happy ending. Tapi ternyata prediksiku salah, hahahaha. Film ini jauh lebih dalam dari itu. Bukan cuma soal cinta, tapi soal ambisi, hidup, waktu, dan pilihan-pilihan yang nggak selalu ideal tapi nyata.
Film ini pelan, hangat, dan diam-diam menghantam perasaan. Bukan yang bikin nangis bombastis, tapi yang bikin dada sesak sambil mikir, “Iya ya, hidup emang kayak gini terkadang manusia harus belajar menerima bahwa tidak semua hal indah harus dimiliki selamanya”
Tentang Anna dan Mimpi Besarnya
Daftar Isi Artikel
ToggleTokoh utama kita adalah Anna De La Vega, perempuan muda asal Amerika yang super ambisius, cerdas, dan terstruktur. Anna ini tipe orang yang hidupnya pakai rencana lima tahunan. Target jelas, langkah jelas, dan mimpi besar: sukses secara akademik dan karier.
Saat akhirnya ia mendapatkan kesempatan kuliah satu tahun di terbaik dunia, University of Oxford, itu seperti pencapaian hidup yang luar biasa. Oxford bukan cuma kampus impian, tapi simbol dari semua kerja kerasnya selama ini. Aku bisa banget relate sama Anna di fase ini, fase di mana kita ngerasa harus “berhasil”, harus membuktikan diri, dan nggak boleh salah langkah.
Dari awal film, Anna digambarkan sebagai sosok yang rasional. Ia datang ke Oxford bukan untuk main-main, bukan untuk cari cinta, apalagi drama. Fokusnya satu: masa depan. Dan di awal film, jelas banget kalau ia datang ke sana dengan mindset: aku nggak boleh gagal.
Di situlah ceritanya mulai menarik.
Oxford yang Bukan Sekadar Latar
Satu hal yang aku suka banget dari My Oxford Year adalah bagaimana Oxford ditampilkan. Kota ini nggak cuma jadi background estetik, tapi benar-benar terasa hidup. Gedung tua, lorong batu, perpustakaan klasik, taman yang tenang, semuanya bikin suasana film jadi reflektif.
Oxford di film ini terasa seperti tempat yang memaksa seseorang untuk berhenti sejenak dan berpikir. Cocok banget dengan konflik batin yang dialami Anna. Ada kesan sunyi tapi hangat, intelektual tapi emosional.
Sebagai penonton, aku ngerasa ikut “tinggal” di sana bareng Anna. Dan itu bikin perjalanan emosional film ini terasa lebih kuat.
Jamie: Sosok yang Datang Tanpa Direncanakan
Lalu masuklah Jamie Davenport.
Jamie adalah kebalikan dari Anna. Ia santai, witty, sedikit sarkastik, dan kelihatannya hidup tanpa terlalu banyak rencana. Tapi justru itu yang bikin karakternya menarik. Jamie bukan cowok romantis klise yang sok sempurna. Ia terasa manusiawi, dengan kehangatan sekaligus sisi misterius.
Pertemuan mereka terasa alami. Nggak instan, nggak lebay. Percakapan mereka ringan, kadang sarkastik, tapi hangat. Chemistry mereka tumbuh lewat obrolan kecil, bukan adegan romantis berlebihan. Aku suka cara film ini membangun hubungan mereka perlahan, seperti hubungan nyata di dunia nyata.
Sebagai penonton, aku nggak merasa “dipaksa” untuk percaya bahwa mereka cocok. Chemistry-nya tumbuh sendiri.
Ketika Cinta Mulai Mengganggu Rencana dan Bertabrakan dengan Ambisi
Yang bikin My Oxford Year terasa relate adalah konflik utamanya: cinta datang di waktu yang nggak ideal.
Anna punya rencana hidup yang jelas. Jamie datang dan secara nggak sadar menggoyahkan semua itu. Dan di sinilah film ini terasa jujur. Nggak ada pilihan yang sepenuhnya benar atau salah. Mau memilih mimpi atau perasaan, dua-duanya punya harga.
Aku suka banget bagaimana film ini nggak mengglorifikasi cinta secara berlebihan. Hubungan Anna dan Jamie bukan solusi dari semua masalah. Justru cinta mereka memunculkan pertanyaan-pertanyaan sulit:
- Apakah aku egois kalau memilih mimpi?
- Apakah aku bodoh kalau memilih cinta?
- Apakah semua hal indah harus dimiliki selamanya?
Dan jujur, pertanyaan-pertanyaan ini kena banget buat aku secara pribadi.
film inipun juga tidak mengglorifikasi pilihan apa pun. Memilih karier bukan berarti dingin dan egois. Memilih cinta bukan berarti lemah. Semua pilihan punya harga, dan kedewasaan adalah berani membayar harga tersebut.
Sebagai penonton, aku tidak merasa digiring untuk membenci keputusan Anna atau Jamie. Justru aku diajak memahami.
Tentang Waktu yang Terbatas
Tanpa terlalu banyak spoiler, film ini punya tema besar tentang waktu. Tentang bagaimana kita sering menganggap waktu itu tak terbatas, sampai akhirnya dihadapkan pada kenyataan sebaliknya.
Film ini juga pelan-pelan mengingatkanku bahwa hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua. Ada momen yang hanya datang sekali. Dan sering kali, kita baru sadar betapa berharganya suatu waktu ketika kita tahu waktu itu tidak akan panjang.
Bagian ini adalah titik di mana My Oxford Year berubah dari sekadar film romantis menjadi film yang reflektif dan emosional. Ada rasa getir yang pelan-pelan masuk. Bukan tragedi yang meledak-ledak, tapi kesedihan yang tenang dan dewasa.
Aku pribadi ngerasa film ini ngajarin satu hal penting:
nggak semua kisah cinta diciptakan untuk bertahan selamanya, tapi bukan berarti ia gagal.
Kadang seseorang hadir di hidup kita untuk mengubah cara kita melihat dunia, bukan untuk tinggal selamanya.
Emosi yang Tenang tapi Dalam
Pacing film ini cenderung lambat. Tapi aku justru menganggap itu sebagai kekuatan. Film ini memberi ruang bagi emosi untuk tumbuh. Tidak terburu-buru, tidak memaksa.
Ada banyak adegan hening yang justru berbicara banyak. Tatapan, senyum kecil, jeda dalam percakapan, semuanya terasa realistis. Seperti kehidupan nyata, di mana perasaan sering kali tidak diucapkan.
Aku merasa film ini mempercayai penontonnya. Tidak semua hal dijelaskan, dan itu membuat pengalaman menontonnya lebih personal.
Secara pribadi, My Oxford Year terasa seperti film yang datang di fase hidup tertentu. Film ini cocok buat kamu yang lagi di persimpangan: antara karier dan perasaan, antara ambisi dan kebahagiaan, antara bertahan dan merelakan.
Aku suka karena film ini nggak sok menggurui. Nggak bilang mana pilihan yang paling benar. Film ini cuma bilang:
setiap pilihan punya konsekuensi, dan kedewasaan adalah berani menerimanya.
Aku juga suka bagaimana Anna sebagai karakter perempuan digambarkan kuat tapi tetap rapuh. Ia bukan “cewek yang diselamatkan cinta”, tapi perempuan yang belajar berdamai dengan perubahan dalam dirinya sendiri. Buat aku, ini representasi perempuan modern yang realistis. Bukan sempurna, tapi berani jujur pada dirinya sendiri.
Jamie, di sisi lain, bukan pahlawan romantis. Ia lebih seperti katalis, orang yang datang untuk mengajarkan cara hidup dengan lebih sadar.
Kekurangan? Tetap Ada
Tentu saja, film ini tidak sempurna. Beberapa konflik terasa bisa digali lebih dalam. Ada momen yang mungkin terasa terlalu “aman” atau terlalu halus. Tapi buat aku, kekurangan itu tidak merusak keseluruhan pengalaman. Karena Film ini bukan tipe yang pengen bikin plot twist besar. Ia lebih fokus ke perasaan, dan itu berhasil.
Well, My Oxford Year adalah film tentang satu tahun yang mengubah hidup seseorang selamanya. Tentang mimpi yang bergeser, cinta yang nggak selalu bisa dimiliki, dan keberanian untuk menjalani hidup apa adanya. Ini bukan film yang akan kamu tonton sambil scrolling HP. Film ini minta kamu untuk hadir, pelan-pelan, dan ikut merasakan.
Buat aku, My Oxford Year adalah pengingat bahwa hidup bukan cuma soal “berhasil”, tapi soal merasakan, mencintai, dan belajar menerima bahwa tidak semua hal indah harus kita genggam selamanya.
Dan kadang, satu tahun di tempat yang tepat, dengan orang yang tepat cukup untuk mengubah cara kita memandang hidup selamanya.
PS : Konten dibuat dengan bantuan AI dengan beberapa perubahan
Source image : Facebook.com